Penulis : Yoedi Wicaksono
Konsep UPFs dan Klasifikasi NOVA
Ultra-Processed Foods (UPFs) semakin banyak mendapat sorotan dalam diskursus gizi dan kesehatan masyarakat. Kehadiran sistem klasifikasi NOVA memperkuat stigma masyarakat bahwa UPFs identik dengan pangan tidak sehat dan hanya berfokus pada keuntungan korporasi semata. NOVA yang membagi pangan berdasarkan tingkat pemrosesan telah membantu advokasi publik, namun juga sering menimbulkan mispersepsi. Banyak konsumen menganggap semua UPFs otomatis buruk bagi kesehatan. Namun, dalam praktiknya, tidak semua UPFs dapat digeneralisasi sebagai pangan yang memberikan dampak berbahaya bagi kesehatan. Faktanya terdapat variasi, sebagian UPFs justru memiliki fungsi vital. Fenomena ini menimbulkan perdebatan ilmiah sekaligus mengakibatkan mispersepsi di kalangan konsumen.
Klasifikasi NOVA membagi pangan menjadi empat kategori: (1) pangan segar/minimal proses, (2) pangan olahan kuliner, (3) pangan olahan, dan (4) pangan ultra-proses (UPFs). UPFs didefinisikan dengan karakter khasnya yaitu adanya formulasi industri, penggunaan aditif, dan melibatkan proses yang kompleks. Kelebihan NOVA adalah kesederhanaannya dan efektif sebagai alat advokasi untuk menyoroti masalah global konsumsi UPFs. Namun, kritik terhadap NOVA juga muncul. Sistem ini terlalu menyamaratakan, tidak membedakan antara UPFs dengan profil gizi buruk dan UPFs yang memiliki fungsi positif. Mispersepsi gizi kemudian tumbuh di masyarakat. Semua UPFs dianggap berbahaya atau sebaliknya, produk UPFs dengan label ‘fortified’ dan ‘low fat’ dianggap setara sehatnya dengan pangan tradisional padahal tidak selalu demikian.
NOVA seharusnya menjadi kritik yang konstruktif bukan destruktif bagi konsep UPFs. NOVA bisa menjadi benang merah bukan menjadi ‘kebenaran absolut’ sesuai misi penemunya yaitu keseimbangan konsumsi antara pangan tradisional dan dominasi UPFs. Hal yang tidak kalah penting adalah memperjuangkan hak kesehatan dan kebutuhan gizi masyarakat dimasa mendatang yang terus berubah mengikuti tantangan zaman.
Realitas Kompleks UPFs dan Pangan Konvensional (Real Food)
Tidak dapat dipungkiri, fakta menunjukkan bahwa UPFs dengan komposisi tertentu berkontribusi pada meningkatnya prevalensi resiko obesitas, diabetes, dan pemicu penyakit gangguan metabolik. Contohnya makanan atau minuman tinggi kandungan gula, garam, lemak, pengawet seperti fast food. Lane et al. (2023) melalui umbrella review menunjukkan korelasi konsumsi UPFs dengan obesitas, diabetes, dan penyakit kardiometabolik. Hamano et al. (2023) membuktikan melalui uji intervensi bahwa diet berbasis UPFs memicu peningkatan berat badan. Di Indonesia, Pratiwi et al. (2021) di Surabaya menemukan konsumsi UPFs berkaitan dengan indeks massa tubuh anak, sementara Colozza et al. (2024) di Yogyakarta menunjukkan adanya fenomena disconnect, masyarakat tahu dampak negatif meski memahami risiko UPFs, konsumsi tetap tinggi karena faktor praktis, harga, dan iklan. Walaupun demikian ada beberapa penelitian atau jurnal serupa dapat dikritisi karena banyak faktor yang perlu dikaji ulang seperti pola makan, gaya hidup, kondisi fisiologi dan latar belakang demografi responden, seperti umur, jenis kelamin, riwayat kesehatan, gaya hidup atau faktor lainnya yang tidak dijelaskan korelasinya.
Jadi data terkesan bersifat subyektif dan seolah-olah menuduh bahwa ‘biangkerok’ utama epidemi hanya UPFs. Tidak semua UPFs bisa digeneralisasi. Beberapa contoh UPFs bersifat fungsional antara lain susu formula bayi sebagai alternatif penting bagi bayi yang tidak bisa mendapat ASI, dan susu bebas laktosa untuk kebutuhan penderita lactose intolerant. Pangan darurat seperti biskuit energi tinggi untuk korban bencana. Pangan instant bernutrisi tinggi khusus ransum tentara saat berperang atau pangan bantuan kemanusiaan kesuatu negara yang mengalami kelaparan, korban perang maupun musibah.
Selain fungsional UPFs yang memadukan aspek sosial budaya juga dibutuhkan seiring perkembangan zaman seperti rendang, opor ayam dan pangan tradisional lainnya dalam kemasan siap saji untuk melestarikan bahkan dapat meningkatkan distribusinya seperti diekspor ke berbagai negara. Ransum selama ibadah umrah atau haji sangat praktis dibutuhkan untuk mencegah kasus traveller diarrea atau keracunan akibat gap waktu preparasi dan penyajian terlalu lama. Hal ini menimbulkan makanan yang disajikan dapur konvensional terkontaminasi bakteri berbahaya penyebab keracunan.
Disisi lain fakta data menunjukkan, kasus keracunan makanan di Indonesia khususnya banyak disebabkan oleh pangan yang disediakan oleh dapur konvensional seperti catering, akibat ketidak tahuan bagaimana preparsi pangan segar dalam jumlah besar.
Menurut berita dari Kementerian Kesehatan (per 2023), kasus keracunan luar biasa (KLB KP) menunjukkan bahwa masakan rumah tangga menjadi sumber utama yang menyumbang sekitar 53 % dari kasus luar biasa tersebut. Data lama (Detik, 2009) menyebut bahwa dalam kasus keracunan makanan di Indonesia, katering 65 %, industri kecil 19 %, dan makanan rumah tangga menyumbang 16 %. Kasus terbaru yang dapat dijadikan contoh yang sangat bagus adalah keracunan Program MBG (Makan Bergizi Gratis). Beberapa data terkait kasus keracunan MBG yang bisa dijadikan ilustrasi.
Hingga 22 September 2025, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat 4.711 kasus keracunan massal terkait program MBG (CNN Indonesia). Versi Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 6.452 orang sebagai korban keracunan MBG hingga September 2025 (Tempo.co). Sebagian laporan lokal menyebut bahwa di Provinsi Jawa Barat saja, ada 20 kasus keracunan MBG yang diinvestigasi Laboratorium Kesehatan setempat (detik.com). Kenapa dalam kasus seperti ini, UPFs tidak dipertanyakan dalam hal yang sama dengan pangan tradisional? atau sebaliknya seolah-olah UPFs dinafikkan kelebihannya pada situasi seperti ini?
Analisis Kritis
Dari berbagai kasus diatas, menunjukkan keterbatasan utama NOVA adalah penyamarataan semua UPFs. Dengan hanya berfokus pada tingkat pemrosesan, sistem ini mengabaikan perbedaan penting dalam profil gizi, keamanan pangan dan fungsi sosial pangan. Akibatnya, susu formula dan snack tinggi gula sama-sama masuk kategori UPFs, padahal dampak kesehatannya berbeda.
Mispersepsi publik pun semakin kompleks. Banyak konsumen percaya bahwa semua UPFs berbahaya, sementara sebagian lain justru menganggap label ‘fortified’ atau ‘low fat’ cukup untuk menjadikan UPFs sehat. Keduanya merupakan bentuk disconnect antara pengetahuan gizi, persepsi, dan praktik konsumsi. Implikasi bagi kebijakan publik, jika semua UPFs dianggap sama, maka intervensi bisa bias, kontraproduktif dan justru merugikan kelompok yang membutuhkan pangan fungsional. Dibutuhkan kerangka evaluasi pangan yang lebih nuansa, yaitu menggabungkan aspek pemrosesan, kandungan gizi, keamanan pangan serta fungsi sosial-ekonomi.
Edukasi gizi berbasis literasi kritis, komunikatif dan bukan sekedar larangan dengan membedakan antara jenis UPFs sangat diperlukan.
Narasi tentang UPFs perlu direkonstruksi. Alih-alih pesan hitam-putih, masyarakat perlu diajak memahami nuansa mana UPFs yang sebaiknya dibatasi, mana yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Kebijakan publik dapat diarahkan pada reformulasi produk industri agar lebih sehat. Modernisasi pangan tradisional agar lebih praktis, seperti jamu kemasan atau tempe chips. Nilai keluarga dan budaya lokal dapat menjadi filter alami untuk menyeimbangkan pilihan pangan, serta mengurangi ketergantungan pada industri UPFs yang beresiko. Ada beberapa aspek penting untuk mengkritisi secara obyektif masalah ini, antara lain :
1. Transparansi dan Label Ganda.
Jangan hanya menggunakan label “UPF” atau kategori NOVA, tapi kombinasikan dengan indikator gizi objektif (misalnya Nutri-Score, Health Star Rating, atau traffic light label gula–garam–lemak). Konsumen bisa tahu, produk ini “UPFs” tapi rendah gula/lemak, atau “minim proses” tapi tetap tinggi garam.
2. Fokus pada Pola Makan, Bukan Produk Tunggal
Edukasi bahwa pola makan keseluruhan (frekuensi, variasi, porsi) lebih menentukan kesehatan daripada satu label “UPFs”. Ajarkan prinsip moderasi, diversifikasi, dan keseimbangan (misalnya 80% minimally processed, 20% convenience food).
3. Edukasi Publik yang Kontekstual
Narasi positif: “lebih banyak sayur, buah, makanan segar” alih-alih hanya “jauhi UPFs”. Konteks lokal: hubungkan dengan budaya makan tradisional Indonesia (tempe, jamu, fermentasi alami) yang selaras dengan prinsip NOVA tapi tetap terjangkau.
4. Kebijakan Publik yang Proporsional
Pemerintah bisa gunakan NOVA sebagai alat analisis tren konsumsi (population level), tapi tidak sebagai satu-satunya dasar regulasi. Hindari regulasi yang menghukum konsumen miskin, yang akses makanannya terbatas ke UPFs murah. Lebih baik insentif subsidi buah, sayur, produk lokal segar ketimbang larangan total.
5. Perspektif Etika dan Religi
Selaras dengan prinsip halalan thayyiban: bukan sekadar halal bahan, tapi juga baik bagi kesehatan, aman, dan tidak berlebihan. Konsumen muslim bisa diberdayakan lewat literasi aditif, mana yang halal, mana yang syubhat.
6. Pendekatan Sains yang Seimbang
Akui bahwa NOVA memberi lensa penting, tapi bukan “kebenaran absolut”. UPFs bukan selalu berbahaya, beberapa bermanfaat untuk ketahanan pangan, fortifikasi zat gizi, atau situasi darurat. Penelitian lanjutan perlu memperhalus klasifikasi agar lebih nyambung dengan health outcomes yang lebih nyata.
Kesimpulan
Klasifikasi NOVA bermanfaat sebagai alat advokasi, tetapi memiliki keterbatasan serius karena cenderung menyamaratakan semua UPFs. Tidak semua UPFs buruk, beberapa justru fungsional dan dibutuhkan. Mispersepsi publik memperkuat stigma negatif atau ilusi sehat, sehingga perlu diluruskan dengan edukasi gizi yang berbasis bukti dan lebih komunikatif.
Solusi jangka panjang meliputi edukasi, regulasi iklan, reformulasi produk dan pengembangan teknologi industri yang lebih baik dan perlunya inovasi pangan tradisional. Dengan demikian, pemahaman gizi masyarakat bisa lebih seimbang, realistis, dan kontekstual.
Solusi yang fair untuk konsumen bukan memilih antara “pro-NOVA” atau “anti-UPF”, tapi edukasi label gizi, memperkuat literasi pola makan, serta kebijakan yang proporsional bagi kelompok rentan. Konsumen berhak mendapat informasi jujur dan praktis, lalu membuat keputusan sesuai kebutuhan, akses, dan konteks sosial-budaya mereka. Hal mendesak lainnya yang dibutuhkan adalah sinergi para ahli teknologi pangan, ahli gizi, ahli kesehatan, pemangku kebijakan dan pihak terkait lainnya. Alih-alih mencari solusi, bukan membuat polemik serta kontroversi penyebab polarisasi ‘si paling penghamba UPFs’ atau ‘si paling natural, sehat dan aman’ yang semakin membingungkan masyarakat awam.
Daftar Pustaka
Monteiro, C. A., Cannon, G., Levy, R. B., et al. (2019). Ultra‑processed foods: what they are and how to identify them. Public Health Nutrition, 22(5), 936–941. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10260459/
Lane, M. M., Davis, J. A., Beattie, S., et al. (2023). Ultra‑processed food exposure and adverse health outcomes: umbrella review. BMJ, 384, e077310. https://www.bmj.com/content/384/bmj-2023-077310
Hamano, S., et al. (2023). Ultra‑processed foods cause weight gain compared with unprocessed diets: a randomized controlled trial. Diabetes, Obesity and Metabolism. https://dom-pubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/dom.15922
Colozza, D., et al. (2024). A qualitative exploration of ultra‑processed foods in Yogyakarta, Indonesia. Public Health Nutrition. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11408947/
Pratiwi, A. A., Chandra, D. N., & Khusun, H. (2021). Association of Ultra‑Processed Food Consumption and Body Mass Index-for-Age among Elementary Students in Surabaya. Indonesian Journal of Public Health Nutrition. https://e-journal.unair.ac.id/AMNT/article/download/24911/17099/152810
Fadly, K., et al. (2023). Fortified Ultra-Processed Foods as an Intervention for Vulnerable Groups. Jurnal Gizi dan Pangan (IPB). https://journal.ipb.ac.id/index.php/jgizipangan/article/view/52777/27159
Vashtianada, A., et al. (2023). Differences of Ultra‑Processed Food Consumption Based on Demographic Factors in Indonesia. Indonesian Journal of Public Health Nutrition. https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1016&context=ijphn
Sakir, N. A. I., et al. (2023). Associations between food consumption/dietary habits and health outcomes in Indonesia. Nutrients. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10861337/



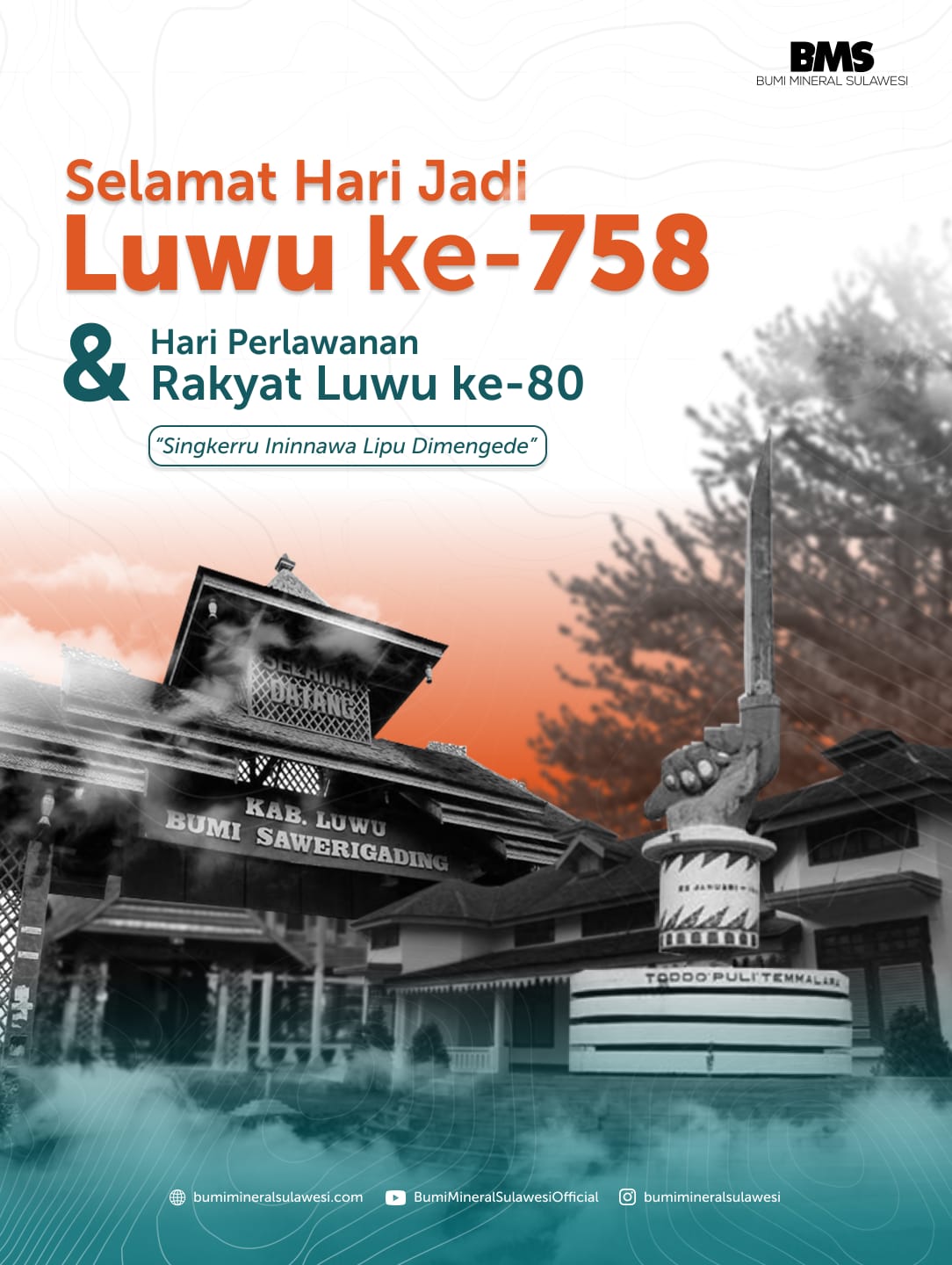



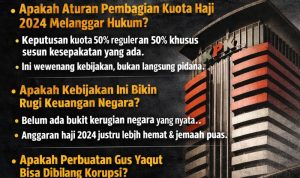
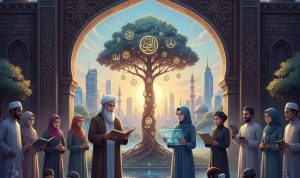

Komentar