Oleh: Dzul Fiqri
OPINI : Dalam persepsi umum, cinta sering kali dimaknai sebagai ledakan emosi, ketertarikan, dan keinginan memiliki. Namun, apakah benar cinta hanya sebatas perasaan? Ataukah ada level yang jauh lebih tinggi, lebih sunyi, namun lebih substansial dari sekadar “merasakan” cinta?
Paradoks Cinta: Ketika Perasaan Tak Lagi Terasa
Sebagian besar dari kita pernah mengalami fase awal jatuh cinta: jantung berdebar, rasa takut kehilangan, dan ketergantungan emosional. Ini adalah fase wajar dan merupakan bagian dari konstruksi psikologis manusia ketika ia terhubung secara emosional terhadap sosok tertentu. Namun, fase ini bukanlah puncak dari cinta.
Dalam pemahaman cinta yang lebih mendalam, terutama dalam perspektif spiritual dan eksistensial, cinta sejati justru terjadi saat tidak ada lagi keinginan memiliki. Saat dua individu menyatu bukan karena rasa ingin memiliki satu sama lain, tetapi karena mereka telah menjadi satu kesatuan jiwa.
Pada titik ini, tidak ada lagi “aku” dan “kamu”—yang ada hanyalah “kita”. Rasa sakit pasangan menjadi rasa sakit diri sendiri, dan menjaga pasangan bukan lagi tugas, melainkan refleksi dari menjaga diri sendiri.
Dinamika Relasi: Dari Ketertarikan Menuju Kesatuan
Banyak pasangan, terutama suami istri yang telah lama hidup bersama, kerap merasakan hilangnya rasa atau gairah. Lalu muncul asumsi bahwa cinta mereka telah hilang. Ini adalah kekeliruan besar dalam paradigma cinta. Sebab, hilangnya rasa bukan berarti hilangnya cinta—justru bisa menjadi pertanda bahwa mereka telah mencapai fase cinta yang lebih dewasa, lebih tenang, dan lebih menyatu.
Dalam psikologi relasi, hal ini dikenal sebagai companionate love, yaitu cinta yang lebih dalam, stabil, dan tidak bergantung pada emosi sesaat. Berbeda dengan passionate love yang meledak-ledak namun cepat padam, cinta yang telah menyatu tak lagi perlu pengakuan harian, karena keberadaannya telah menjadi bagian dari identitas masing-masing.
Kesalahan Umum: Meninggalkan Saat Rasa Hilang
Kesalahan fatal dalam memahami cinta adalah mengasumsikan bahwa hilangnya perasaan harus diikuti dengan perpisahan. Padahal, dalam banyak kasus, perasaan itu tidak hilang—ia hanya telah berubah bentuk. Ketika pasangan memutuskan untuk berpisah hanya karena merasa “tak lagi mencintai”, mereka sering kali jatuh pada fase penyesalan dan kerinduan, yang menyadarkan bahwa cinta mereka belum selesai, hanya salah dimaknai.
Tentang Cinta Sepihak: Muncul, Lalu Menjauh
Cinta yang tidak terbalas—atau dalam istilah lokal Luwu Raya dikenal sebagai cinta kalena (cikal)—sering membuat seseorang terjebak dalam pusaran emosi yang menyakitkan. Namun, berdasarkan pendekatan teoritis penulis, ada cara untuk memancing benih cinta dalam diri orang lain: muncullah sebentar, lalu menjauh.
Teori ini berangkat dari prinsip law of psychological reactance—manusia cenderung lebih menghargai sesuatu yang sulit dijangkau. Dengan menampakkan cinta dan kemudian menjauh, seseorang memicu rasa kehilangan pada pihak yang dituju. Ketika rasa rindu mulai tumbuh, di situlah cinta memiliki peluang untuk muncul.
Kesimpulan: Cinta yang Sejati Adalah Cinta yang Telah Menyatu
Kesempurnaan cinta bukanlah saat perasaan membuncah, tetapi justru saat perasaan itu tidak lagi dirasakan karena telah menyatu dalam keseharian. Cinta bukan lagi tentang memiliki, tetapi tentang menjadi. Menjadi satu kesatuan dalam suka dan duka, dalam tawa dan luka.
Dalam dunia yang dibanjiri dengan ekspektasi dan romantisasi hubungan, kita perlu mendobrak mainset lama bahwa cinta hanya indah saat terasa. Nyatanya, cinta yang sejati justru muncul ketika dua hati telah melebur menjadi satu, dan tidak lagi saling mencintai secara sadar—karena cinta itu telah menjadi ada dalam setiap detik kehidupan mereka.

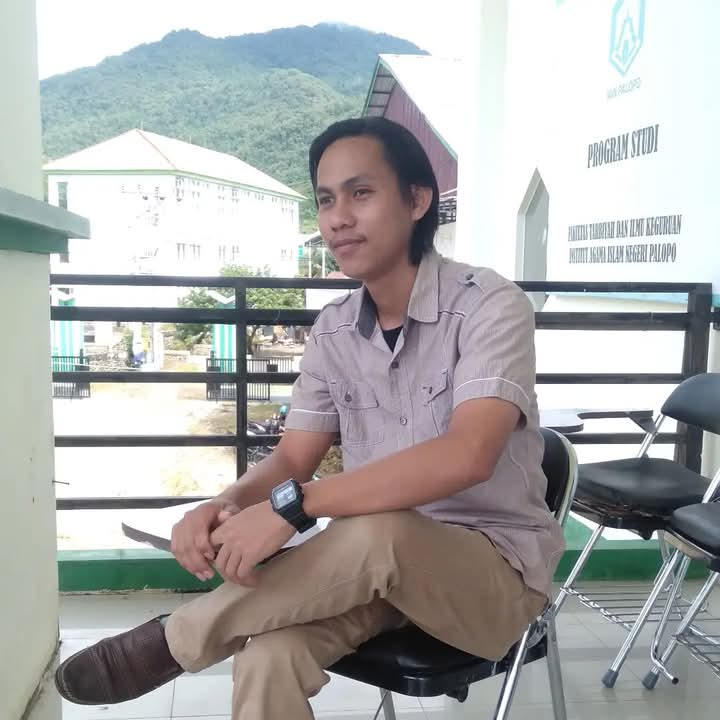









Komentar